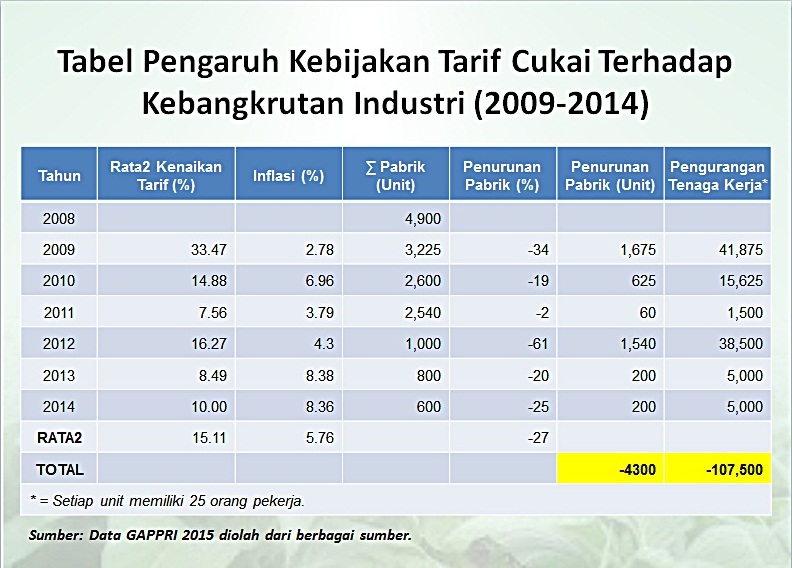“Dio, kamu di mana?”
Saya mengirim pesan pendek pada Sabda Armandio. Siang itu, saya sudah satu taksi dengan Panjul dan Dhani dan menunggu Dio di Taman Suropati, Menteng. Kami berempat rencananya akan pergi bareng ke bandara Soekarno Hatta. Kemudian terbang ke Lombok.
Pesan saya tak berbalas. Saya mencoba menelpon Dio. Lagi. Sudah empat kali saya coba. Masih tidak aktif. Saya melongok jam di pergelangan tangan kiri. Sudah jam 13.20.
“Sampe setengah dua dia gak ada, kita tinggal ya,” kata saya pada Panjul dan Dhani.
“Palingan hapenya sengaja dimatiin buat hemat baterai,” kata Panjul.
Bisa jadi. Sekitar 30 menit lalu, saya sempat menelpon Dio. Ia sedang di kereta, dari Bogor menuju Cikini. Dio baru ingat kalau dompet dan KTPnya ada di rumahnya, bukan di kosannya yang terletak di Cikini. Maka dengan gegas ia menuju Bogor. Setelah selesai, ia langsung menuju Cikini untuk kemudian ke Taman Suropati.
Saat saya telepon, penulis novel Kamu ini sudah di Lenteng Agung. Dari Lenteng Agung ke Cikini harusnya tak makan waktu lama. Normalnya hanya 15 menit saja.
Pukul 13.30 akhirnya tiba. Kami terpaksa meninggalkan Dio. Waktu itu kami berpikir, mending satu orang yang ketinggalan pesawat daripada empat orang yang ketinggalan. Pahit memang.
Pesawat kami menuju Lombok berangkat pada 15.45. Taksi akhirnya meninggalkan Taman Suropati.
Baru saja jalan sepelemparan batu, ada pesan Whatsapp masuk. Dari Vira, salah satu peserta ke Lombok. Ia bilang sedang ada di sekitar Menteng. Mengajak untuk bareng. Kami setuju. Janjian ketemu di Taman Menteng. Akhirnya kami putar balik.
“Nanti ternyata pas kita jemput Vira, si Dio sms kalau udah di Taman Suropati,” kata Panjul berkelakar.
Haram jadah. Ternyata kelakar Bapak Air Mata Nasional itu jadi kenyataan. Saat menuju Taman Menteng, Dio kirim pesan Whatsapp: aku udah di Taman Suropati.
Saya ngakak.
Akhirnya kami jadi menjemput Dio. Vira akhirnya langsung menuju bandara. Saat ketemu Dio, dia bilang hapenya sengaja dimatikan agar hemat baterai, sesuai perkiraan Panjul.
Giliran Panjul yang ngakak.
***
Kami pergi ke Lombok untuk mengikuti acara Jelajah Negeri Tembakau. Ini adalah perjalanan untuk mengenal dunia tembakau dan juga industrinya. Mulai dari hulu hingga hilir. Dari kebun hingga menuju pabrik. Biasanya acara ini berada di Jawa. Di daerah-daerah penghasil tembakau terkenal, mulai dari Temanggung hingga Kudus. Kali ini dipusatkan di Lombok, sentra penghasil tembakau Virginia FC di Indonesia.
Ada 15 orang blogger yang ikut serta. Kebanyakan dari Jakarta. Tapi ada pula yang dari Bandung, Jogja, dan Surabaya. Beberapa orang adalah kawan lama. Sebagian lagi sudah saya kenal tapi belum pernah ketemu. Sisanya, saya belum pernah kenal dan ditemukan di Lombok.
Kami sampai di Lombok pada pukul 8 malam waktu setempat. Suasana bandara internasional Praya nyaris tak jauh beda saat saya datang ke sana pertama kali bareng mas Iqbal Aji Daryono, sang seleb Facebook yang fenomenal itu.
Di luar bandara, ada banyak orang menunggu sanak saudara yang datang. Beberapa menggelar tikar dan duduk lesehan. Sebagian ada yang menunggu di bak mobil. Otentik dan sangat Indonesia sekali. Menyenangkan.
Sebuah bus mini lantas membawa kami ke pusat kota Mataram. Normalnya sekitar 40 menit perjalanan. Tapi malam itu sang supir memilih untuk menyetir dengan hati-hati. Saking pelannya kadang bikin gemas. Kami maklum kalau perjalanan ini molor hingga 1 jam.
Rombongan Bandung, Jogja, dan Surabaya datang menyusul. Setelah makan malam, kami ngobrol sejenak. Tentang agenda acara. Juga bagi-bagi kaos dan buku yang dibawa dari Jogja. Oh ya, saya sekamar dengan Ayos.
Bertahun yang silam, kami menempuh rute Jember-Flores dengan motor, dan tak sanggup menginap di hotel. Malam ini, kami tidur di hotel. Gratis.
***
Hari pertama, lagi-lagi, kami diguncang kepanikan. Pagi baru saja dimulai. Nasi goreng dan sereal belum usai digulung usus. Tapi panik sudah datang karena ada dua orang peserta ternyata belum ada di bus saat semua sudah siap berangkat. Siapa gerangan?
Dio dan Bang Dede.
Mereka sekamar. Dan mungkin perpaduan yang sangat cocok. Bang Dede gemar bercerita, dan Dio gemar mendengarkan. Saya membayangkan mereka ngobrol ngalor ngidul sampai pagi. Tidur. Lalu terlambat bangun.
Benar saja. Setelah ditelpon berkali-kali, dengan nada panik mereka bilang akan segera keluar. Lima menit setelahnya, tampaklah Bang Dede dan Dio dengan wajah bantal, mata yang bengkak –mengingatkan saya pada Panjul setelah menangis– dan muka bersalah.
“Dio habis diapain aja sama Bang Dede?” kata Tekno Bolang.
Yang disebut hanya cengar cengir saja.
Agenda pertama hari itu adalah pergi ke gudang Djarum di Montong Gamang, Lombok Tengah. Rencananya kami akan belajar tentang ilmu dasar tembakau dan juga proses sortasi dan pengemasan.
Bisa dibilang gudang Djarum ini adalah tahap akhir perjalanan tembakau di Lombok. Setelah disortasi, tembakau yang lolos standar akan langsung dikemas dan dibawa ke Kudus, markas besar Djarum, untuk kemudian diproses lebih lanjut.
Kami ditemui oleh Pak Iskandar, Senior Manager Djarum di Lombok. Kami sudah bertahun tak bertemu, sejak saya menulis tentang beliau. Tak ada yang berbeda dari Pak Iskandar. Masih ramah. Suka tertawa.
Kami lantas diajak ke lantai dua kantor Djarum. Di sana ada ruang rapat. Disediakan pula berteko teh dan kopi. Namanya juga di pabrik rokok, ya jelas ada rokok produk Djarum. Berslop. Semua bisa diambil gratis.
Beberapa di antara peserta, salah satunya si Farchan, terlihat membawa berbungkus rokok.
“Buat temen di kantor, Ran,” katanya nyengir.
Saya ketawa saja.
Oh ya, sekadar pemberitahuan saja. Dari 15 orang peserta, sebagian besar tidak merokok. Kinkin, Vira, Ayos, Agus Mulyadi, Dhani, dan saya sendiri, adalah beberapa orang yang tidak merokok.
Pak Iskandar menjelaskan tentang sejarah penanaman tembakau di Lombok. Bagian ini mungkin akan saya tunda dulu. Saya sedang menulis lebih panjang tentang tembakau di Lombok untuk situs Pindai.
Saya melongok Mbak Vira Indohoy yang setia dengan buku sketsa. Ia tampak serius menggambar Pak Iskandar, sambil sesekali nanya ini dan itu.
Di sudut belakang, ada Agus Mulyadi yang tekun menyimak penjelasan Pak Iskandar. Agus memang blogger yang taat dan tekun. Beda bener jika dibandingkan dengan Panjul yang malah asyik main game. Ya sambil sesekali menangis, tentu. Bang Dede beberapa kali menanyakan perihal tembakau di Lombok. Mulai perihal harga dan juga jenis tembakau. Ayos juga khusyuk menyimak penjelasan Pak Iskandar.
“Melihat beliau, aku jadi inget bapakku,” kata Ayos, yang bapaknya sudah 30 tahunan bekerja di sektor kopi.
Presentasi Pak Iskandar sedikit membingungkan bagi para peserta. Beliau mengira kalau yang datang kali ini sudah tahu tentang tembakau. Padahal sebagian besar dari mereka, kalau tak mau menyebut seluruhnya, masih awam soal tembakau. Apa yang dipresentasikan oleh Pak Iskandar, boleh dibilang, adalah versi advance. Versi lanjut.
Melihat para peserta yang agak bingung, Pak Iskandar mengambil langkah strategis: membawa kami ke tempat sortasi serta pengemasan tembakau.
Para petani biasanya sudah mengemas daun tembakau dalam anyaman tikar pandan. Gulungan tembakau yang sudah dikeringkan itu akan dibawa ke pintu pertama. Di pintu itu, sudah ada para grader.
Menyaksikan para grader bekerja, seperti melihat para maestro yang menguasai ilmu ghaib. Mereka bisa mengetahui nilai tembakau hanya dari bentuk dan baunya saja. Sesekali mereka perlu mengecek kondisi daun. Kalau dianggap kurang kering, maka daun tembakau akan dikeringkan ulang di oven milik Djarum.
Grading tembakau ini bukan perihal mudah. Kata Pak Dawam, tangan kanan Pak Iskandar, grading tembakau bisa mencapai 56 tingkat. Meski sekarang sudah disederhanakan, jumlah grading masih mencapai 20-an. Rumit dan perlu waktu panjang untuk belajar. Sama sekali bukan hal ghaib.
Setelah melewati proses grading, tembakau yang lolos seleksi akan dikumpulkan dan dikemas dalam tikar pandan. Bisa langsung masuk truk untuk kemudian dibawa menuju Kudus.
![DSCF6139.resized]()
Para pekerja di gudang Djarum Foto oleh: Farchan Noor Rachman
Ada pula tembakau yang tidak lolos seleksi pertama. Biasanya ada sedikit cacat pada daun tembakaunya. Ada proses sortasi berikutnya untuk daun tembakau seperti ini.
Prosesnya manual. Dipilah dan dipilih oleh ibu-ibu yang berdiri dengan sabar dan tekun di depan sabuk berjalan. Di atas sabuk itu ada jejeran daun tembakau bergerak cepat. Tembakau yang masih memenuhi syarat akan dikumpulkan untuk kemudian dikemas dan dibawa ke Kudus. Sedangkan yang kurang bagus akan dikumpulkan dan digunakan untuk berbagai keperluan.
Setiap musim panen, pemandangan di gudang Djarum ini akan selalu sama: para petani yang berdatangan dan menunggu uang cair. Setiap hari, uang yang beredar ke petani bisa mencapai Rp 6 miliar sehari!
Di dalam gudang, para pekerja sibuk bekerja dengan tekun. Walau sama sekali tidak robotik. Mereka masih bercanda dan sesekali duduk santai. Setiap musim panen, ada sekitar 400 tenaga kerja di gudang ini. Mereka bekerja di bagian sortasi hingga pengangkutan.
***
![DCIM166GOPRO]()
Hamparan ladang tembakau Foto oleh: Syukron
Perjalanan dilanjutkan ke Pademare. Ini salah satu desa pusat tembakau. Sepanjang mata memandang, ada daun tembakau hijau yang ranum.
Di tempat ini, para peserta diajak untuk ngobrol dengan petani. Juga melihat oven. Banyak yang kaget ketika tahu kalau ovennya berukuran besar. Tingginya bisa 7 meter. Di dalam oven ini ada pipa-pipa yang mengalirkan panas. Sebutannya adalah flue. Karena itu tembakau Virginia di Lombok dikenal sebagai Virginia FC, alias Virginia Flue Cured.
Di Pademare, kami disuguhi kelapa muda yang baru dipetik dari pohon. Saat itu Panjul mengeluh ada yang berbeda dari rasa air kelapa mudanya.
![nuran]()
Panjul yang meminum air matanya sendiri Foto oleh: Atre
“Kenapa emang?”
“Gak tau nih, rasanya agak asin.”
Saya mencicipinya sedikit. Benar, sedikit asin. Padahal punya saya rasanya biasa saja. Perasaan saya tak enak. Saya menengok ke wajah Panjul. Bedebah, ternyata ia mulai menitikkan air mata. Katanya ia terharu melihat tembakau tumbuh subur. Itu yang saya minum bukan air kelapa, melainkan air mata Panjul.
Dasar bandot tengik.
Setelah puas melihat tembakau, oven, dan minum kelapa muda, kami jelas foto bersama. Yang membedakan, foto kali ini diambil oleh drone yang dibawa oleh Syukron. Kapan lagi foto narsis dengan peralatan mahal.
Perjalanan belum usai. Malam itu kami makan malam di Taliwang Raya, sebuah rumah makan yang menyajikan ayam Taliwang dan Sop Bebalungan sebagai hidangan andalan.
Di sini kami bertemu dengan Pak Martadinata, budayawan Sasak yang juga merupakan seorang dosen. Beliau yang datang dengan baju serta peci putih dan sarung berwarna gelap ini banyak menceritakan tentang hikayat tembakau di Lombok dan masyarakatnya.
Tembakau, bagi masyarakat Sasak, menempati posisi sebagai tanaman yang dimuliakan. Tak kalah dengan padi. Karena menghormati tembakau, ada tradisi roah. Yakni syukuran sebelum mulai menggarap lahan. Para petani biasanya berkumpul, dan akan memanjatkan doa bersama. Berharap agar hasil panen bagus.
Ada pula tradisi besiru, yakni bergotong royong tanpa dibayar. Biasanya dilakukan ketika ada pembangunan rumah atau panen. Meski tak dibayar, para peserta besiru “wajib” disuguhi rokok.
“Rasanya gak sopan kalau gak ada rokok,” ujar Pak Martadinata.
***
Hari kedua, Dio dan Bang Dede tak mau terperosok di lubang yang sama: kesiangan sampai tak sempat sarapan. Mereka bangun lebih pagi.
Yang tidak bangun malah duo begundal: Arman Dhani dan Panjul. Dhani sejak kemarin malam masuk angin. Sudah biasa. Huek huek sepanjang malam, kata Panjul.
“Gue pikir dia mau mati cuk, udah gue bacain Al Fatihah di kupingnya,” tambahnya.
Kalau Panjul terlambat bangun karena kemarin malam pergi ke Senggigi sendiri. Ngapain? Pakai nanya pula. Ya nangis laaaaaah. Jadi kalau ada ahli oseanografi, sila dicek. Pasti ketinggian air laut Senggigi akan bertambah lumayan drastis. Itulah hasil air mata Panjul.
Tapi untungnya mereka berdua tak jadi ditinggal. Dengan tergopoh-gopoh, mereka berlari ke bus. Dhani malah sempat mencomot pisang sebelum naik ke bus.
Agenda hari ini adalah ke Desa Lekor. Ini desa yang kerap diceritakan oleh Pak Iskandar karena termasuk desa yang berubah karena tembakau.
“Dulu desa ini bukan Lekor. Tapi desa tertinggal,” kata Haji Sabarudin, tetua Desa Lekor.
Desa ini termasuk desa legendaris. Dulu, dikenal sebagai desa rampok. Setiap ada orang kerampokan, pasti orang Lekor dituduh menjadi dalang. Jalan menuju desa ini dulu tak beraspal.
Semua berubah sejak tembakau masuk. Hasil panen tembakaunya bagus. Kebetulan pula tanah Desa Lekor adalah tanah yang disukai tembakau: kering, tapi masih ada sumber air yang cukup.
Walau begitu, beberapa kali para petani tembakau sempat gagal panen karena curah hujan yang terlalu tinggi. Tapi karena tembakau memberikan begitu banyak harapan, nyaris tak ada warga yang undur diri. Mereka masih terus menanam tembakau.
Kini Desa Lekor tak lagi dikenal sebagai desa para pencoleng. Desa mereka lebih dikenal sebagai desa penghasil tembakau kualitas wahid.
Di Lekor, agenda kerja kami resmi berakhir. Selanjutnya adalah bersenang-senang! Kami pergi ke Sade, desa adat Sasak yang masih memegang teguh tradisi. Juga ke Pantai Tanjung Aan. Malam ini agendanya adalah mengantar Kinkin yang harus pulang karena Senin tak boleh telat kerja. Lalu dipungkasi dengan makan nasi puyung yang pedas dan ntap itu.
***
Esok subuhnya, dengan mata masih terkantuk, kami harus keluar dari hotel. Ini Senin subuh. Sebagian besar di antara kami harus bekerja. Kembali ke dunia nyata.
Sampai jumpa lagi, Lombok. []
Post-scriptum:
Terima kasih untuk para teman-teman yang bersedia mengikuti acara ini.
1. Ayos Purwoaji (Surabaya)
2. Arman Dhani (Jakarta)
3. Agus Magelangan (Jogja)
4. Aditia Purnomo (Jakarta)
5. Astri Apriyani (Jakarta)
6. Sukma Dede (Jakarta)
7. Wira Nurmansyah (Jakarta)
8. Farchan Noor Rachman (Jakarta)
9. Sabda Armandio Alif (Jakarta)
10. Maharsi Kinkin (Jakarta)
11. Eddward S. Kennedy (Jakarta)
12. Tekno Bolang (Jakarta)
13. Syukron Makmun (Bandung)
14. Vira Indohoy (Jakarta)
15. Indri Juwono (Jakarta)
Postingan kawan-kawan yang lain:
Sabda Armandio: Jelajah Tembakau Nusantara: Tembakau Lombok
Tekno Bolang: Lombok, Jelajah Negeri Tembakau
Farchan Noor Rachman: Daulat Negeri Tembakau
Vira Indohoy: Another Side of Lombok Island, West Nusa Tenggara
Agus Mulyadi: Jelajah Negeri Tembakau Lombok
Wira Nurmansyah: Negeri Tembakau Lombok
Indri Juwono: Hamparan Hijau Tembakau Lombok
Sukma Dede: Gunung, Pantai, Tenun, hingga Tembakau Ada di Lombok
Atre: Tembakau Terbaik di Pulau Lombok dan Jelajah Lombok
Eddward S. Kennedy: Menelusuri Tembakau dan Air Mata di Lombok
Aditia Purnomo: Lombok Sebelum dan Sesudah Tembakau dan Memaksimalkan Potensi Tembakau Lombok
Maharsi Wahyu: Semerbak Negeri Tembakau
Video oleh Kang Eko: Jelajah Negeri Tembakau Lombok